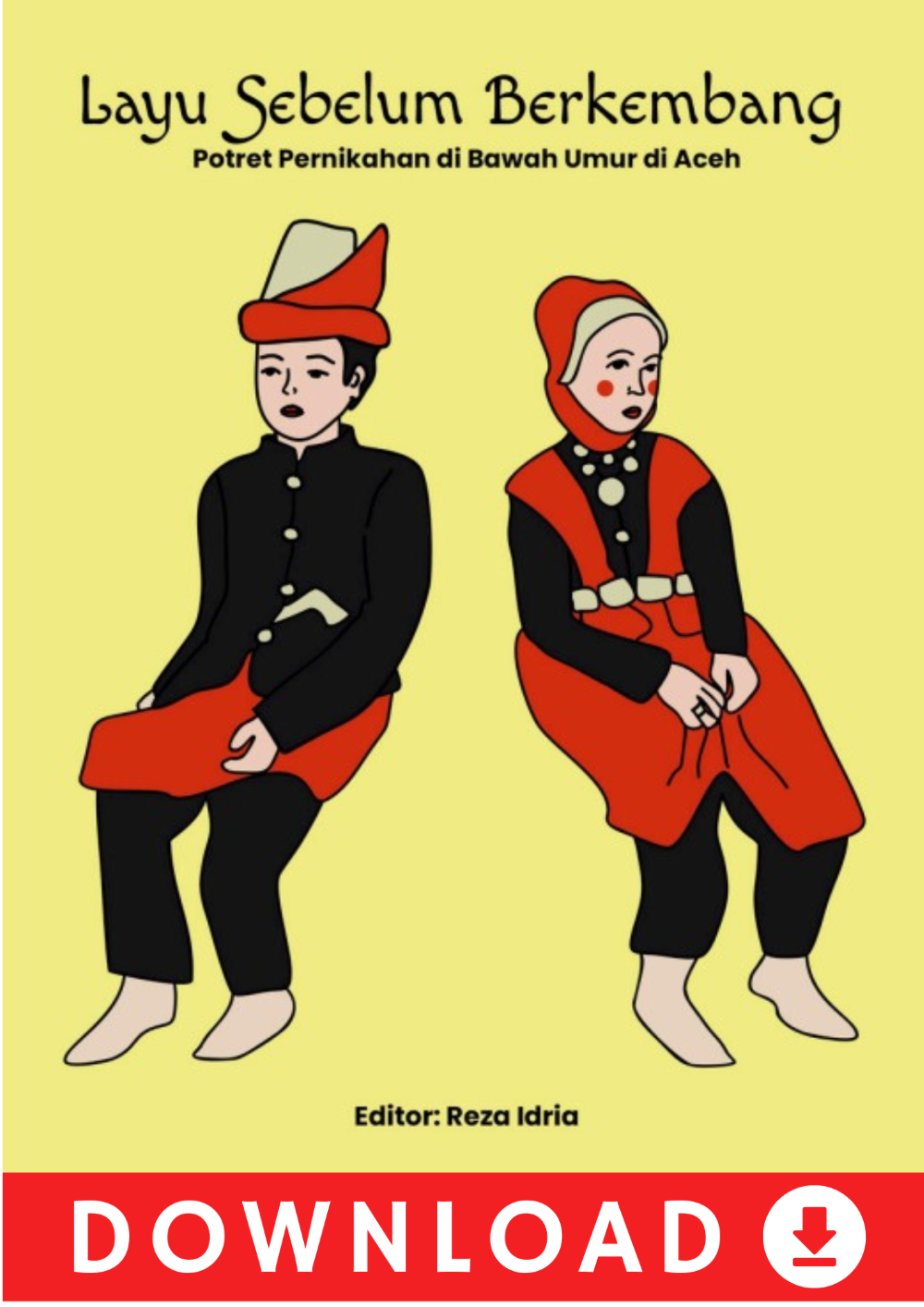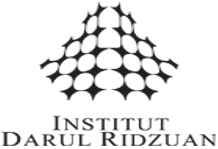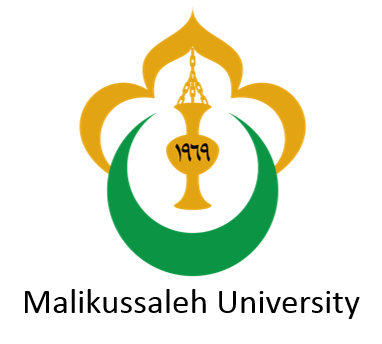Oleh : Arfiansyah
Penulis adalah Program Manager ICAIOS dan
Dosen Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry

Laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa semenjak tahun 2004 hingga tahun 2017, KPK telah mengeksekusi 497 koruptor dari berbagai kalangan. Di luar angka tersebut, KPK sedang melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan proses hukum lainnya terhadap banyak pelaku lain yang telah ditangkap. HIngga saat ini, KPK terus memperhatikan transaksi politik yang berlangsung di berbagai daerah. Di Aceh sendiri, kasus paling mutakhir dan masih hangat hingga saat ini adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, BUpati Bener Meriah, Ahmadi, dan beberapa orang lain yang disinyalir terlibat dalam proses suap proyek Dana Otonomi Khusus. Dengan demikian sejauh ini KPK telah menangkap sebanyak 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD dan 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia (Kompas.com). Melihat denomena ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla bahkan mengatakan bahwa Indonesia mencetak rekor dunia untuk jumlah koruptor yang ditangkap.
Dengan jumlah koruptor yang ditangkap sedemikian banyak dan selalu menjadi sorotan publik, nampaknya KPK belum mampu memberikan efek jera terhadap pejabat publik lainnya sehingga praktik korupsi terus terjadi. Penulis berpendapat, ada dua hal yang menjadi penyebabnya yaitu: mahalnya biaya politik, dan terbentuknya budaya korupsi.
Biaya Politik
Semenjak lengsernya Orde Baru, kekuasaan di seluruh Indonesia berpusat dan terkonsentrasi di Jakarta. Dengan sistem kekuasaan yang bersifat otoriter, kekuasaan negara berada di tangan sekelompok kecil. Konon dikuasai oleh mereka-mereka yang berada di Cendana dan “guritanya.” Mereka mengintervensi kegiatan politik dan proses pergantian kepemimpinan politik di daerah-daerah. Intervensi yang tinggi tersebut membuat biaya politik di daerah menjadi kecil.
Bergantian sistem politik dari otoritarianisme ke demokrasi telah merubah banyak hal. Pemerintah pusat tidak lagi secara lansung memberikan kontribusi finansial dan otoritas politik dalam pemilihan dan penentuan kepala daerah. Partai pengusung tidak mungkin memberikan bantuan dana penuh untuk semua kandidat gubernur/bupati di daerah-daerah. Kandidat harus berpikir keras untuk mendapatkan dana kampanye untuk memenangkan pemilihan. Ini membuat dana politik menjadi sangat mahal.
Dengan mahalnya dana politik saat ini maka yang berpotensi besar untuk maju berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang sanggup membiayai sebagian atau seluruh dana kampanye yang diperlukan. Untuk itu biasanya mereka bekerja sama dengan pemilik modal kaya raya yang bersedia membantu dengan ikatan perjanjian tertentu. Hal ini setali tiga uang dengan pemilihan anggota legislatif.
Pengeluaran dana politik yang besar menyebabkan seorang yang memenangi pemilihan umum terpaksa melakukan setidaknya dua hal. Pertama, memenuhi kontrak perjanjian dengan pemberi modal. Kedua, menjaga emosi konstituen atau pendukung mereka yang tiba-tiba bertambah berkali lipat ketika mereka berkuasa. Gaji bulanan seorang kepala daerah atau anggota dewan tidak akan cukup untuk membalas budi. Sumber satu-satunya adalah uang negara yang bisa didapat melalui otoritas politik. Uang negara tersebut tersebar dalam berbagai bentuk, seperti proyek pembangunan, dana aspirasi, izin usaha dan lain sebagainya.
Selain dana pemerintah, pejabat negara juga kerap menggunakan dana sosial untuk dana politik. Michel Buehler (2008), dalam amatannya di Sulawesi Utara, menemukan beberapa bupati mengusung isu penerapan syariat Islam dan pembentukan badan zakat dalam kampanyenya. Setelah menang, ia merealisasikan janjinya dengan membentuk badan zakat di bawah kendali penuh pemerintah. Dengan demikian selain menimbulkan citra islami, bupati mudah mengumpulkan dana politik melalui dana ummat berbentuk zakat, sedekah dan infaq. Zakat kemudian menjadi sumber dana politik untuk memuluskan dan mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya, memenuhi kebutuhan konstituen, serta membalas jasa tim sukses dan para donator.
Dengan keadaan yang seperti ini, bisa dipastikan bahwa proses politik di Indonesia akan selalu menciptakan oligarki baru dari kalangan pemilik modal yang berhasrat untuk meningkatkan kekayaan mereka melalui otoritas politik. Politik dalam situasi seperti ini tidak ubahnya seperti berbisnis di mana kandidat harus mengeluarkan modal besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan situasi seperti ini, kecil kemungkinan proses politik di negeri ini menghasilkan pemimpin yang bersih. Hanya orang “super gila” yang mau menghabiskan seluruh kekayaannya untuk kepentingan rakyat dengan cara menjadi kepala daerah dan anggota legislatif. Mereka yang waras dan rasional kecil kemungkinan mengikuti proses ini. Mereka memiliki banyak pilihan untuk membantu rakyat tanpa harus terlibat dalam permainan siap kaya atau miskin.
Budaya Korupsi
Dengan penguasaan kekayaan/uang negara melalui ororitas politik, masyarakat percaya bahwa untuk menyelesaikan urusan di lembaga pemerintah dan ekonomi/kesejahteraan, mereka harus berdekatan atau berhubungan dengan penyelenggara negara. Kita kerap mendapati masyarakat baik dari kalangan agamawan maupun pengangguran, mengantar proposal fiktif ke berbagai insitusi pemerintahan. Mereka mendatangi rumah-rumah para elit politik dan birokrat hanya untuk meminta “ongkos tiket pulang” ke kampung halaman mereka. Perilaku ini memaksa elite politik dan birokrat untuk memikirkan sumber dana ekstra. Dari mana sumber dana ekstra selain gaji bulanan, bonus dan sumber yang sah lainnya apabila bukan dengan menipulasi projek, dana aspirasi, dan lainnya? Dengan demikian, masyarakat juga mendorong para politisi dan penyelengara negara untuk melakukan korupsi. Malangnya ketika pejabat ditangkap KPK, masyarakat pula yang merundung mereka habis-habisan.
Tekanan terhadap politisi sebagai sumber ekonomi masyarakat meningkat ketika pemerintah belum berhasil mendatangkan investor sebagai alternatif sumber ekonomi selain sebagai petani dan PNS. Anehnya ketika beberapa investor menanamkan modalnya, sering kali masyarakat melakukan penolakan dengan memungut “Pajak Nanggroe” bahkan sebelum pabrik berdiri. Terkadang juga sampai melakukan kekerasan. Sehingga sumber ekonomi satu-satunya adalah uang negara yang membuat tekanan terhadap elite, sebagai jembatan terhadap sumber tersebut, tidak berkurang.
Keluarga-keluarga juga kerap mendorong anggota keluarga mereka yang potensial untuk memasuki dunia politik dan berhubungan dengan pemerintahan. Memiliki anggota keluarga yang berada di lingkaran pemerintahan, bahkan hukum, dipandang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan. Minimalnya, memiliki anggota keluarga besar yang dekat dengan kekuasaan menjadi kebanggaan yang tidak hanya mengangkat martabat tapi juga kesejahteraan dan keamanan (sebagai backing). Situasi sosial ini masih sangat kentara dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Masyrakat seperti ini masih banyak di Aceh dan Indonesia.
Penutup
Keadaan sosial dan politik seperti tergambar di atas, mendorong tumbuh dan berkembangnya perilaku korupsi di Indonesia yang tidak akan habis meski otoritas KPK diperbesar sekali pun. Dengan tuntutan sosial dan politik seperti ini pula, pekerjaan dan publikasi keberhasilan KPK menangkap koruptor hanya akan menjadi peringatan bagi para pelaku lainnya untuk lebih berhati-hati dan cerdik. Ini karena permasalahan utama korupsi bukanlah pada mental yang rakus, gaya hidup, kurang taat beragama, dan kepribadian lainnya. Akan tetapi pada sistem politik yang membutuhkan dana besar dan budaya korupsi yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Kedua hal ini mengakibatkan siapapun yang memasuki dunia politik kemungkinan besar akan melakukan korupsi baik skala kecil maupun besar. Ini juga mengambarkan bahwa motif berkuasa (menjadi kepala daerah, anggota legislatif dan sebagainya) hanyalah motif penguasaan terhadap sumber ekonomi. Siapa pun dan apa pun ideologi partai politiknya; apa pun jargon politik dan kampanyenya apakah syari’ah, nasionalis, liberalis, komunis atau lainnya; tujuannya tetap sama, menguasai sumber ekonomi negara.
Sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pemilihan penyelengara negara. Penulis berpendapat, hal ini antara lain dapat dilakukan dengan membiaya biaya politik selama proses kampanye atau mengembalikan semua biaya politik pemenang pemilihan. Dengan kata lain, proses politik harus didanai oleh uang rakyat, bukan oleh uang pribadi seperti yang terjadi selama ini. Dengan uang rakyat, maka kontrol rakyat terhadap pemerintahan kemungkinan akan semakin tinggi. Pekerjaan KPK pun kemudian hanya membersihkan politikus-politikus benar-benar kotor dan tidak dipusingkan akan kemungkinan munculnya politikus kotor di generasi berikutnya. Selama dana politik bersumber dari uang pribadi, sekiranya tidak adil menghukum koruptor dengan hukuman yang berat. Karena selain melakukan bisnis, yaitu mengeluarkan modal pribadi yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mereka juga di bawah tekanan donatur, partai pendukung, konstituen dan masyarakat yang berpikir bahwa mereka adalah jembatan untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara.