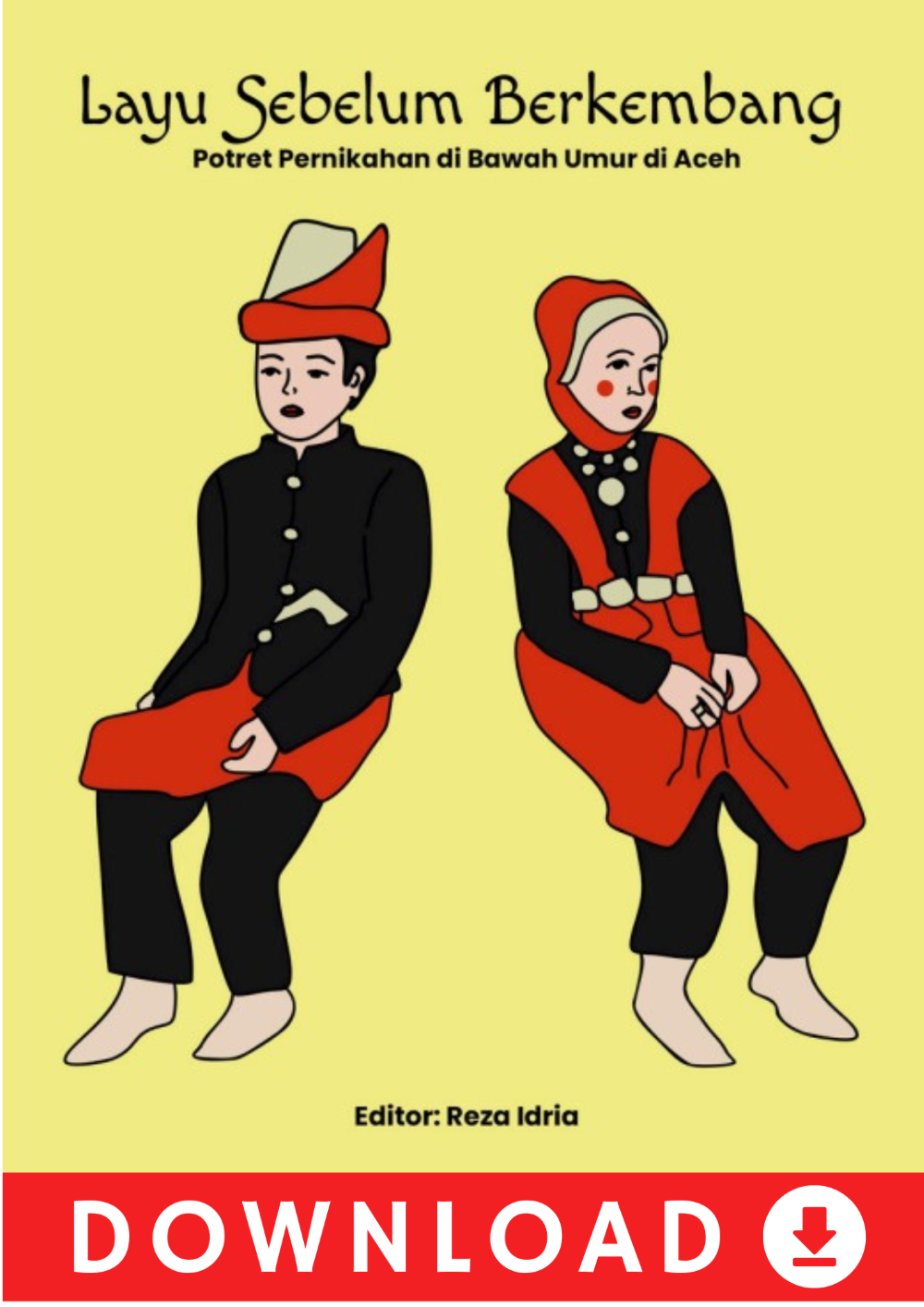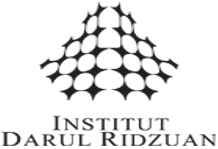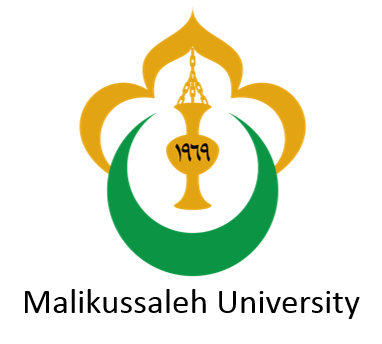MEMUTUS MATA RANTAI KORUPSI
Oleh : Arfiansyah
Penulis adalah Program Manager ICAIOS dan
Dosen Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry

Laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa semenjak tahun 2004 hingga tahun 2017, KPK telah mengeksekusi 497 koruptor dari berbagai kalangan. Di luar angka tersebut, KPK sedang melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan proses hukum lainnya terhadap banyak pelaku lain yang telah ditangkap. HIngga saat ini, KPK terus memperhatikan transaksi politik yang berlangsung di berbagai daerah. Di Aceh sendiri, kasus paling mutakhir dan masih hangat hingga saat ini adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, BUpati Bener Meriah, Ahmadi, dan beberapa orang lain yang disinyalir terlibat dalam proses suap proyek Dana Otonomi Khusus. Dengan demikian sejauh ini KPK telah menangkap sebanyak 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD dan 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia (Kompas.com). Melihat denomena ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla bahkan mengatakan bahwa Indonesia mencetak rekor dunia untuk jumlah koruptor yang ditangkap.
Dengan jumlah koruptor yang ditangkap sedemikian banyak dan selalu menjadi sorotan publik, nampaknya KPK belum mampu memberikan efek jera terhadap pejabat publik lainnya sehingga praktik korupsi terus terjadi. Penulis berpendapat, ada dua hal yang menjadi penyebabnya yaitu: mahalnya biaya politik, dan terbentuknya budaya korupsi.
Biaya Politik
Semenjak lengsernya Orde Baru, kekuasaan di seluruh Indonesia berpusat dan terkonsentrasi di Jakarta. Dengan sistem kekuasaan yang bersifat otoriter, kekuasaan negara berada di tangan sekelompok kecil. Konon dikuasai oleh mereka-mereka yang berada di Cendana dan “guritanya.” Mereka mengintervensi kegiatan politik dan proses pergantian kepemimpinan politik di daerah-daerah. Intervensi yang tinggi tersebut membuat biaya politik di daerah menjadi kecil.